Ponpes.net – Hingga hari ini, isu Penguatan Karakter yang diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang delapan jam belajar dengan lima hari sekolah masih menuai pro-kontra. Meski Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Karakter yang menganulir Permendikbud tersebut, publik tetap saja ribut.
Namun, tulisan ini tak hendak memasuki arena perdebatan tersebut. Penulis justru ingin memperkenalkan kepada masyarakat tentang sebuah kitab berisi penguatan karakter (baca: akhlak/tata krama) ala kaum Nahdliyin (sebutan warga NU). Sejatinya, penguatan karakter melalui pendidikan dasar telah dilakukan kaum Nahdliyin melalui Madrasah Diniyah (Madin) ratusan tahun silam.
Soal karakter atau akhlak, masih lekat dalam ingatan penulis saat belajar tentang pendidikan akhlak di Madin 25 tahun silam. Pendidikan akhlak tersebut diajarkan melalui syi’iran (syair) yang penulis masih hafal beberapa bait hingga hari ini. Berikut bait-bait syair tersebut:
iki syi’ir kanggo bocah lanang wadon # nebihake tingkah laku ingkang awon
sarto nerangake budi kang prayogo # kanggo dalan podo mlebu ing suwargo
bocah iku wiwit umur pitung taun # kudu ajar toto keben ora getun
(Syiir ini untuk anak laki-laki dan perempuan, untuk menjauhkan dari perbuatan yang tercela. Serta menerangkan budi pekerti yang baik, sebagai jalan menuju surga. Anak itu sejak usia tujuh tahun, harus belajar tata karma supaya kelak tidak menyesal).
Tiga bait syair tersebut sangat membekas di hati sanubari penulis. Goresan kata yang indah ini hendak mematri pesan bahwa sejak dini kita musti belajar tata krama agar kita menjadi orang berkarakter kuat di masa mendatang. Penulis merasa, ajaran luhur melalui syi’iran tersebut menjadi bekal utama dalam mengarungi kehidupan di masa kini. Bahkan, masih terus relevan hingga masa-masa mendatang.
Rasa penasaran dan keinginan mengenang masa remaja yang penuh jadual sekolah, baik pagi maupun sore, membuat penulis kembali menelaah kitab tersebut. Belakangan, penulis tahu bahwa kitab syi’ir Ngudi Susilo ini dikarang oleh Allahuyarham KH Bisri Musthofa Rembang, ayahanda Mustasyar PBNU KH A Musthofa Bisri.
Kitab berisi 84 bait tersebut merupakan kitab berbahasa Jawa dalam bentuk sya’ir (puisi). Nama lengkapnya, Syi’ir Ngudi Susilo Suko Pitedah Kanthi Terwelo (Syair Belajar Akhlak yang memberi Petunjuk dengan Jelas). Buku antologi syi’iran berisi pelajaran budi pekerti atau akhlak ini ditulis Mbah Bisri Musthofa di Rembang, Jawa Tengah, pada bulan Jumadil Akhir 1373 H (1954 M).
Kitab tersebut kemudian dicetak oleh Penerbit Menara Kudus, di Kudus Jawa Tengah. Hampir seluruh madin di Jawa Tengah dan sebagian pondok pesantren menjadikan Syiir ini sebagai mata pelajaran hafalan untuk tingkat dasar. Teknik belajar di pesantren atau madin memang mengedepankan sistem hafalan. Sebab, sda kaidah yang menyebut bahwa pemahaman tak akan sempurna tanpa menghafal. Tegasnya, hafalan justru menguatkan pemahaman. Pada titik tertentu, hafalan juga bisa mengasah kecerdasan.
Satu hal yang penulis ingat, syiir ini didendangkan dengan irama membahagiakan. Kata Pak Guru waktu itu, irama yang digunakan adalah Bahar Rajaz yang diadopsi dari sastra Arab. Hal tersebut meneladani Nabi Muhammad sewaktu menyiapkan Perang Khandaq. Rasulullah SAW menggali parit sembari bernyanyi/bersyair riang gembira bersama para sahabat dengan irama Bahar Rajaz tersebut.
Berbakti kepada orang tua
Kudu tresno ring ibune kang ngerumati # kawit cilik marang bopo kang gemati
Ibu bopo rewangono lamun repot # ojo koyo wong gemagus ingkang wangkot
Lamun ibu bopo prentah inggal tandang # ojo bantah ojo sengol ojo mampang
Di bab-bab awal, KH Bisri Musthofa menjelaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua (ortu). Kata beliau, anak harus cinta kepada ibu yang telah merawat sejak kecil, juga pada ayah yang telah memberikan belain kasih sayang. Jika keduanya sibuk, sebagai anak kita harus membantu mereka. Jangan diam saja seperti anak sok kecakepan nan sombong. Lalu, jika ibu dan ayah memerintahkan sesuatu (selama tidak bertentangan dengan perintah agama) segeralah memenuhinya, jangan membantah sembari menunjukkan wajah marah.
Sudah tentu, bait-bait pertama ini seolah menyindir siapa saja yang berani melawan orang tua. Hemat penulis, karakter ini penting ditanamkan sejak dini kepada anak. Bait keempat, kelima dan keenam juga mendahulukan ibu daripada bapak. Ini juga pelajaran utama yang harus dikenang. Pasalnya, Rasulullah sendiri saat ditanya siapa yang musti dihormati, menjawab “ibumu” hingga tiga kali. Memang, derajat sang ibu lebih tinggi tiga tingkat dibanding ayah. Yakni, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Tiga tugas inilah yang tak mungkin tergantikan oleh siapapun.
Kemudian, sejak awal kita diingatkan agar juga menaruh hormat kepada orang tua lainnya. Terpenting lagi, kita diajari agar berkata dengan orang tua harus dengan halus dan pelan, namun jelas. Tidak boleh kasar, berkata jorok, dan marah-marah. Kalau orang tua duduk di bawah, jangan sampai anak duduk di atas. Jika orang tua tidur tidak boleh ramai. Kalau lagi membaca dipelankan, kalau lewat di depan orang tua harus punya tata karma. Kalau orang tua marah lebih baik diam, jangan mendebat.
Jika karakter dasar tersebut sudah tertanam kuat di benak sang anak, ke depan tinggal mengingatkan sembari menguatkan kembali jika teledor. Sikap-sikap terpuji ini sudah dikenalkan dan dipraktikkan sejak anak-anak belajar di madin. Tak berlebihan jika soal penguatan karakter ini menjadi tradisi lama bagi kaum Nahdliyin.
Relevansi penguatan karakter
Setelah menunjukkan tata krama kepada orang tua sebagaimana penulis paparkan di atas, Mbah Bisri Musthofa kemudian menguraikan isi kitab berikutnya dengan menurunkan tujuh bab penting, yakni: cara membagi waktu, adab di sekolah, adab di rumah/pulang sekolah, adab bersama guru, adab jika ada tamu, sikap/ perilaku yang sopan, dan cita-cita luhur. Nilai-nilai karakter positif dalam kitab besutan Mbah Bisri Musthofa tersebut pada titik tertentu memiliki relevansi penguatan karakter dalam “Nawa Cita” Jokowi.
Pada titik ini, penulis sepakat dengan Jauhar Hatta (2013) yang menyebut adanya sejumlah benang merah dari seluruh muatan kitab syi’ir tersebut jika dikaitkan dengan 18 karakter yang dikembangkan pemerintah sebagaimana dicanangkan Kemendikbud.
Pertama, religius. Sebagaimana termaktub dalam syair berikut:
kenthong subuh inggal tangi nuli adus # wudlu nuli sholat khusuk ingkang bagus
rampung sholat tandang gawe opo bahe # kang prayogo koyo nyaponi omahe
lamun ora iyo moco-moco quran # najan namung sithik dadiyo wiridan
budal ngaji awan bengi sekabehe # toto kromo lan adabe podo bahe
(Jika masuk waktu shubuh segera bangun lalu mandi, wudlu, kemudian sholat dengan khusyu’. Setelah sholat lalu beraktivitas apa saja yang baik seperti menyapu rumah. Jika tidak, bacalah Al-Qur’an, meski hanya sedikit hendaknya menjadi kebiasaan. Berangkat ke tempat mencari ilmu, baik siang maupun malam, sama saja tata krama dan adabnya).
Kedua, jujur. Perhatikan syair berikut:
Wahid Hasyim santri pondok gak sekolah # dadi mentri karo liyan ora kalah
kabeh mau gumantung ing sejo luhur # kanthi ngudi ilmu sarto laku jujur
(Wahid Hasyim santri pondok yang tidak sekolah, bisa jadi menteri dengan yang lain tidak kalah. Semua itu tergantung niat luhurnya, dengan disertai upaya mencari ilmu dan perilaku jujur).
Di bait-bait selanjutnya, Hatta yang juga Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dengan teliti menemukan benang merah isi syair kitab ini dengan isu-isu kekinian. Misalnya toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, dan aneka karakter positif lainnya. Sudah tentu, isi kitab tersebut relevan sekali dengan pengembangan dunia pendidikan saat ini, terutama dalam penanaman akhlak, dan pengembangan karakter anak.
Hal penting lainnya adalah pemakaian syair/lagu sebagai sarana pembelajaran dan pelestarian budaya daerah, khususnya bahasa Jawa. Ini menjadi kekuatan untuk terus menjaga kearifan lokal (local wisdom).
Kehadiran kitab Syi’ir Ngudi Susilo merupakan khazanah berharga bagi perkembangan karya tulis di Nusantara. Bangsa Indonesia, khususnya di pulau Jawa, sejak lama memakai syi’ir sebagai salah satu media pembelajaran. Banyak hal yang bisa diteladani dari kitab syair karya orator ulung asal Rembang ini. Satu di antaranya adalah pembelajaran dan penguatan karakter bagi anak didik.
Saran penulis, Mendikbud beserta jajarannya berkenan membaca sekaligus menelaah kitab sederhana namun membahana ini. Tak hanya Dirjen Pendidikan, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud mestinya turut melap-lap “intan permata” ini. Kalau perlu, kitab tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia agar bangsa ini bisa memetik inspirasi untuk membangun negeri.
Sumber: nu.or.id




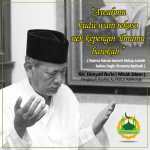







Yuk komen